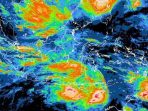- Birokrasi Membunuh Aksi Iklim Lokal: Kisah Penjaga Alam yang Terabaikan di Tengah Janji Global - 18/11/2025
- LKM Idealis 2025 Bahas Krisis Iklim: Jaring Nusa Dorong Kepekaan Sosial dan Advokasi Mahasiswa - 13/11/2025
- Resmi Punya Ketua Baru, IKA FKM Unhas Dipimpin Dr. Azri Rasul dengan Fokus Perkuat Jaringan Alumni - 13/11/2025
Klihijau.com – Di tengah riuh rendah sorak-sorai dan janji-janji ambisius di Konferensi Iklim COP 30 di Belém do Pará, Brazil—tempat wacana pendanaan iklim global dan nasional kembali dipintal—tersimpan sebuah ironi yang menusuk hingga ke jantung desa dan hutan adat.
Sementara triliunan dolar digulirkan dalam narasi penyelamatan planet, suara-suara dan tangan-tangan yang paling gigih menjaga ekosistem justru nyaris tak terjamah oleh aliran dana tersebut. Sebuah kajian mendalam dari International Institute for Environment and Development (IIED) menjadi cermin yang getir atas ketimpangan ini.
Bahwa hanya sekitar 10 persen pendanaan iklim yang sampai di kampung-kampung dan Masyarakat Adat. Ini berdasarkan penelitian International Institute for Environment and Development (IIED) yang menemukan bahwa dari total US$17,4 miliar yang disetujui untuk proyek iklim (2003–2016), hanya sekitar US$1,5 miliar (kurang dari 10 persen) diarahkan untuk aktivitas di tingkat lokal. Seringkali hambatan utama adalah birokrasi.
Padahal, Masyarakat Adat dan masyarakat lokal yang ada di kampung-kampung tersebutlah yang menjaga alam, sekaligus yang paling terdampak oleh krisis iklim.
“Kami mempercayakan pengelolaan dana kepada Masyarakat Adat dan membantu prosesnya, mulai dari penulisan proposal sampai menjaga bukti pembayaran untuk akuntabilitas dan lain sebagainya. Jadi bukan mempersulit, tapi mempermudah,” kata Bustar Maitar, CEO Yayasan EcoNusa, dalam Diskusi Nexus Tiga Krisis Planet tentang Utang Ekologis dan Keadilan Pendanaan Iklim, Selasa, 18 November 2025. di Kantor Celios, Menteng, Jakarta.
Ia mencontohkan, Masyarakat Adat di Raja Ampat, Papua yang memiliki homestay kesulitan membangun kembali homestay mereka yang rusak karena tidak beroperasi sepanjang pandemi Covid-19 karena kesulitan mendapatkan pendanaan. Padahal, homestay tersebut merupakan sumber penghidupan mereka untuk membiayai kebutuhan sehari-hari hingga membayar biaya sekolah anak.
“Padahal kalau mendapat pendanaan dan bisnisnya berjalan kembali, masyarakat mau mengembalikan dana tersebut. Jadi bukan minta. Dan merekalah yang selama ini menjaga terumbu karang, menjaga hutan di sana,” ujarnya.
Bustar juga menyinggung tentang rencana mempercepat pengakuan hutan adat seluas 1,4 juta hektare hingga 2029 yang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ucapkan saat pembukaan konferensi iklim COP 30 di Brazil. Proses verifikasi hutan adat tersebut juga membutuhkan pembiayaan yang besar.
“Kalau misalnya komitmen dana yang disampaikan negara-negara maju bisa jalan, proses pengakuan ini bisa lebih cepat,” katanya.
Tanti Budi Suryani, Program Manager Dana Nusantara menambahkan, hal yang sama telah Dana Nusantara lakukan kepada mitra-mitra utama selama dua tahun terakhir dan sudah mendukung 450 inisiatif yang sangat erat dengan perjuangan hak-hak mereka.
“Cara aksesnya mudah, dilandasi saling percaya, dan bentuknya hibah,” ujarnya.
Dana Nusantara berdiri atas inisiatif tiga lembaga, yakni Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) untuk mendukung berbagai upaya dan inisiatif dari Masyarakat Adat, petani, nelayan, perempuan, dan generasi muda, utamanya dalam memecahkan tantangan pengakuan hak tenurial, dan mengelola tanah, air, wilayah, lingkungan hidup.
Tanti menyebut ada pengalaman pahit dari salah satu komunitas di Kalimantan Timur, yang pernah dijanjikan akan mendapatkan pendanaan karbon sekitar Rp40 juta. Namun, setelah masyarakat melestarikan hutan di wilayah adatnya dan programnya telah berlangsung selama lima tahun, masyarakat tetap tidak bisa mendapatkan dana tersebut. “Persoalannya adalah birokrasi yang panjang,” ujarnya.
Tanti menyebut bahwa Masyarakat Adat di Asia mengelola 40 persen dari lahan yang ada, tapi Masyarakat Adat hanya mendapatkan pengakuan hukum atas wilayahnya dari pemerintah sekitar 10 persen.
Negara Maju Seharusnya Membayar Utang Ekologis
Dalam pembukaan COP 30-UNFCCC di Belem, Brasil pada 10 November 2025, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell menuntut komitmen negara-negara maju dalam pendanaan iklim. Komitmen tersebut penting untuk memastikan kelangsungan hidup manusia, planet, dan masa depan.
Namun, program global yang seharusnya membantu negara berkembang menghadapi perubahan iklim tersebut justru sudah melenceng dari komitmen awal. Alih-alih membayar utang tersebut melalui hibah, mayoritas pendanaan iklim yang dijanjikan justru diberikan dalam bentuk pinjaman.
Padahal beberapa negara, terutama negara berkembang, hanya memiliki APBN terbatas dan memiliki banyak persoalan lain yang perlu diselesaikan, seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan. Sehingga budget untuk mitigasi iklim sangat terbatas.
“Dalam kesepakatan Paris, disebutkan bahwa negara maju juga memiliki mandat untuk membantu negara berkembang. Jadi bukan hanya memberikan akses, tapi bahkan pendanaannya,” kata Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios)
Bhima mengatakan pendanaan iklim yang terjadi selama ini justru memperkaya negara kaya, menambah utang negara miskin, dan gagal memberikan manfaat lingkungan yang dijanjikan.
Hasil investigasi Reuters, menunjukkan bahwa isu perubahan iklim dimanfaatkan sebagai peluang bisnis baru. Negara maju membeli surat utang negara berkembang dengan imbal hasil tinggi 6–10 persen, atau mengikat negara berkembang dalam program transisi yang sarat pinjaman seperti JETP.
“Sebenarnya ada yang menikmati krisis iklim. Krisis iklimnya makin p
arah, profitnya makin tinggi,” ujarnya.
Negara-negara maju, kata Bhima memiliki utang ekologis historis sejak revolusi industri. Mereka menggunakan batubara, mengeksploitasi sumber daya alam, serta melakukan investasi beremisi tinggi di negara berkembang.
Namun selain memberikan pendanaan iklim dalam bentuk pinjaman, beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Jerman, juga menyalurkan hibah dengan berbagai syarat, termasuk menggunakan teknologi maupun konsultan dari negara maju, yang pada akhirnya menguntungkan perusahaan dan konsultan dari negara maju sendiri.
Menurut Bhima, pemerintah mestinya mengubah paradigma bahwa dana restoratif hanya berasal dari utang dari luar negeri maupun menjual kredit karbon. Pemerintah seharusnya juga berkomitmen untuk menagih utang pendanaan iklim kepada negara-negara maju tersebut.
“Ini bisa menjawab keadilan dalam sistem pendanaan iklim,” sambungnya. Termasuk dari bank-bank BUMN dan swasta yang belum membayarkan dosa-dosa iklimnya namun terus menyalurkan pinjaman kepada sektor ekstraktif.
Bhima menambahkan, International Court of Justice pun sudah menyampaikan bahwa negara yang mensponsori kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab, memberikan repartisipasi, dan memulihkan kerusakan yang mereka sebabkan.
“Jika mereka terus melakukan perusakan lingkungan, mereka bisa dibawa ke mahkamah internasional,” kuncinya.